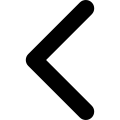Menimbang Soeharto Setelah 27 Tahun Reformasi
Menimbang Soeharto Setelah 27 Tahun Reformasi

Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.Dua Sosok Pembentuk Indonesia ModernDalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Lihat komentar